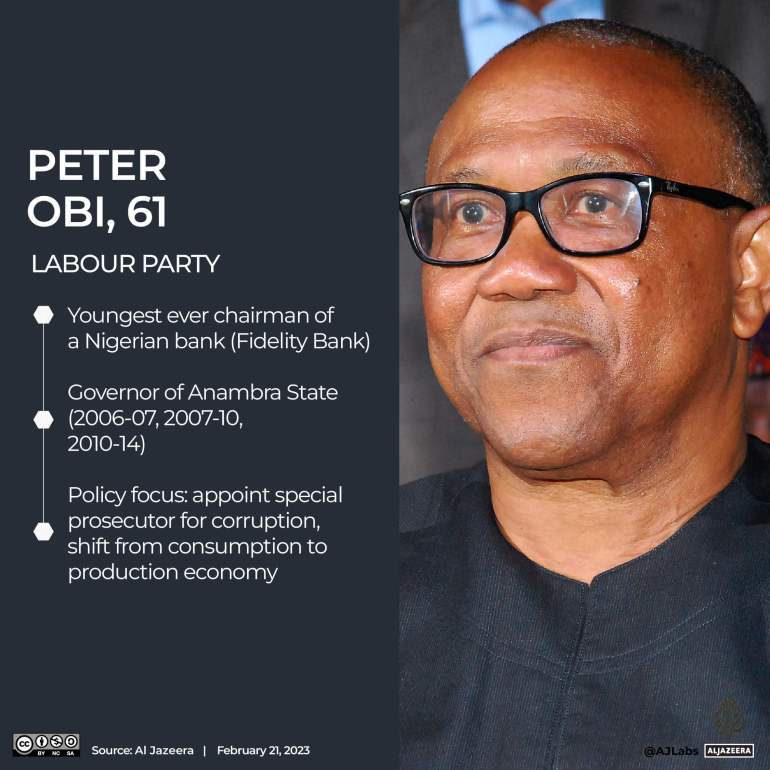Beberapa bulan yang lalu, pada hari yang dimulai sebagai hari biasa di Beograd, saya menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak saya kenal.
Saya ragu untuk menjawab. Saya berasal dari Yaman. Saya ditahan di Guantanamo selama 15 tahun tanpa pernah dituntut melakukan kejahatan. Saya akhirnya dibebaskan pada tahun 2016 dan ditempatkan di Serbia, tetapi saya masih membawa bekas luka dari pemenjaraan saya yang tidak adil. Jadi saya waspada terhadap panggilan dari nomor tak dikenal.
Tetapi pada hari itu saya mengangkat telepon dan menjawab, “Salaam alaykum, halo?”
Ketika saya mengenali suara di akhir baris, saya berjuang untuk menahan air mata.
Itu adalah Saifullah Paracha – tahanan tertua di Guantanamo yang merupakan ayah kedua bagi saya selama bertahun-tahun di kamp penjara.
“Selamat datang, selamat datang yang datang,” aku bernyanyi keras ke ponselku dalam bahasa Arab, menyapanya dengan lagu yang kami nyanyikan bersama di Guantanamo.
Mendengar suara Saifullah lagi setelah hampir tujuh tahun, untuk pertama kalinya sejak saya meninggalkan Guantanamo, membuat hati saya hidup dan gembira. Dia masih memiliki tawa yang sama, tawa yang sangat aku rindukan.
“Apa kabarmu?” Dia bertanya.
“Aku sangat senang, wallahi,” jawabku. “Terima kasih Allah atas pembebasanmu.”
Setelah menghabiskan hampir dua dekade di penjara, Saifullah akhirnya dibebaskan pada Oktober 2022. Ia kembali ke negara asalnya, Pakistan. Dia sekarang tinggal di sana bersama keluarganya.
Saya memintanya untuk menyalakan video agar saya bisa melihat wajahnya lagi. Apa yang saya lihat di layar ponsel saya memberi saya perasaan campur aduk. Saya sangat senang bahwa dia ada di rumah, di mana dia berada, dikelilingi oleh keluarganya. Tetapi pada saat yang sama, saya sangat sedih melihat bagaimana penjara telah menua selama beberapa tahun terakhir.
Penjara mencuri hidupmu dan menghancurkan jiwamu. Bukan penjara itu sendiri tentunya, tapi orang-orang yang memenjarakanmu. Mata Saifullah terlihat lelah, dan wajahnya menunjukkan tanda-tanda tahun-tahun yang telah dicuri darinya. Tapi untungnya, dia tidak kehilangan selera humornya, sifat pedulinya, atau pandangan hidupnya yang ceria. Dia masih pria yang sama yang saya cintai sama seperti ayah saya sendiri.
Saifullah benar-benar ayah kedua bagi saya. Dan seperti ayah mana pun, pada panggilan pertama kami setelah bertahun-tahun berpisah, dia bertanya apakah saya sudah menikah. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya sedang menunggu dia keluar dari penjara sehingga dia bisa menghadiri pernikahan saya.
Kami kemudian berbicara tentang saya untuk beberapa waktu buku – Saya mengiriminya salinan ke Guantanamo, tetapi dia tidak diizinkan memilikinya. Dia juga bertanya tentang pendidikan saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya telah menerima gelar sarjana saya dan akan segera menyelesaikan gelar master di bidang manajemen. Wajahnya berseri-seri saat aku berbicara, aku tahu dia bangga padaku.
Dia kemudian bertanya kepada saya tentang saudara-saudara lain yang telah dibebaskan sebelum dia, dan berbagi kabar tentang mereka yang masih ditahan di Guantanamo.
Masing-masing dari kami jelas dalam pikirannya.
Di Guantanamo, Saifullah adalah ayah, guru, pembimbing, koki, terapis, dan mediator kami dengan administrasi kamp penjara.
Dia sering memberi tahu kami bahwa dia menganggap semua orang di kamp – baik tahanan maupun staf – sebagai “anak-anaknya”. Karena itu, semua orang, termasuk semua penjaga, memanggilnya “ayah” atau “shasha”.
Dia mencurahkan seluruh waktu dan energinya untuk membantu orang lain – tidak hanya narapidana, tetapi juga penjaga dan staf lainnya.
Dia memiliki kelasnya sendiri di kamp enam. Di ruang kelas darurat yang diubah dari sel, dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengajar mata pelajaran dan keterampilan yang berbeda kepada kelompok narapidana yang berbeda. Dia mengajar banyak narapidana bahasa Inggris dan keterampilan bisnis selama berada di sana.
Dia memiliki pengaruh besar pada kehidupan para tahanan. Dia memiliki pengaruh besar dalam hidup saya.
Saya tidak diizinkan menemuinya sampai saya meninggalkan Guantanamo pada tahun 2016. Meninggalkan kamp tanpa pamit padanya adalah salah satu hal tersulit yang harus saya lakukan. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkannya. Saya berharap dia bisa menggantikan saya dan pergi – saya akan dengan senang hati tinggal di kamp jika itu berarti dia akan dibebaskan.
Sejak saya pergi, saya dengan cemas menunggu kabar pembebasannya.
Saya ingin mengiriminya surat melalui Komite Palang Merah Internasional, tetapi pengacara saya memperingatkan saya bahwa komunikasi semacam itu dapat digunakan untuk melawan dia dan orang lain, jadi saya tetap diam.
Ketika saya mendapat kabar bahwa dia akan segera dibebaskan, saya tidak bisa menahan kegembiraan saya. Pada malam pesawat yang membawanya lepas landas dari pangkalan militer Guantanamo, saya ditandai di sebuah posting di Twitter yang mencantumkan nomor penerbangannya. Saya menonton pesawat online sepanjang malam. Hanya dua jam setelah pesawatnya mendarat, saya mendapat konfirmasi bahwa dia memang ada di rumah, di Pakistan.
Saya sangat senang. Rasanya seperti saya sendiri telah dibebaskan. Saya senang dia keluar hidup-hidup, bahwa dia bisa melihat keluarganya. Saya senang dia akan mengalami kehidupan di luar Guantanamo lagi.
Saya memposting kabar baik di grup WhatsApp mantan narapidana – semua orang sangat gembira. Sama seperti saya, mereka semua merasa bahwa ayah mereka sendiri telah dibebaskan.
Setelah panggilan pertama saya dengan Saifullah, saya memposting di grup obrolan lagi untuk memberi tahu semua orang bahwa ayah kami mengirim salam kepada mereka. Mereka semua menanyakan detail kontaknya agar mereka dapat berbicara dengannya juga, dan menanyakan tentang kesehatannya.
Mereka juga menanyakan apakah Shasha telah menyampaikan kabar tentang saudara-saudara kita yang masih berada di Guantanamo.
Itulah ironi menjadi mantan tahanan Guantanamo. Selama bertahun-tahun kami terjebak di kamp itu, sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi di dunia. Tapi sekarang kami bebas, kami sama-sama putus asa untuk berita dari penjara – dari saudara yang harus kami tinggalkan.
Hari ini saya bersyukur – kami semua – bahwa ayah kami, Saifullah, akhirnya pulang. Saya bersyukur bisa melihat wajahnya lagi, mendengar tawanya dan meminta nasihatnya saat saya membutuhkan.
Tapi perjuangan kita untuk keadilan masih jauh dari selesai.
Pastor Saifullah ditahan di AS tanpa pengadilan atau dakwaan selama hampir dua dekade. Dia kehilangan bisnisnya. Dia kehilangan kesehatannya. Keluarganya sangat menderita – beberapa anaknya harus tumbuh tanpa benar-benar mengenal ayah mereka.
Dia sekarang sudah kembali ke rumah, tetapi dia masih menghadapi banyak tantangan sebagai akibat dari apa yang telah dilakukan padanya.
Akankah mereka yang memenjarakannya secara salah melakukan sesuatu untuk membantunya menetap dan membangun kembali hidupnya? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa pemerintah AS menghancurkan hidupnya – itu menghancurkan seluruh hidup kita. Namun Washington jelas tidak berniat menebus kejahatan yang telah dilakukannya terhadap kami.
Meninggalkan Guantanamo tidak berarti Anda bebas, atau Anda bisa mulai menjalani hidup Anda. Faktanya adalah jika Anda pernah dipenjara di Guantanamo, tempat itu tetap menjadi bagian dari hidup Anda selamanya. Tahun-tahun penyiksaan dan pelecehan meninggalkan luka permanen di tubuh dan jiwa Anda. Saya ingin tahu apakah ada di antara kita yang akan pulih dari trauma yang menimpa kita di kamp itu.
Sama seperti Saifullah, semua mantan tahanan Guantanamo terus menderita dalam satu atau lain cara. Kita semua mencoba memproses trauma kita dan menyesuaikan diri dengan realitas baru kita. Beberapa dari kita masih di penjara di negara Lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Yang lain hidup dalam limbo, tanpa status atau hak hukum apa pun, di negara-negara seperti Kazakstan. Tanpa ada yang membantu mereka menyembuhkan dan membangun kembali kehidupan mereka, beberapa menjadi tunawisma di negara asal mereka atau negara ketiga tempat mereka dikirim setelah dibebaskan. Beberapa kehilangan nyawa mereka karena kelalaian medis.
Hari ini kita tampaknya bebas, tetapi kita semua sebenarnya hidup di Guantanamo 2.0. Setelah beberapa dekade pelecehan, AS mencampakkan kami begitu saja dan tidak menawarkan dukungan, perawatan, atau kompensasi. Banyak yang menderita di negara-negara yang seharusnya tidak pernah mereka kirimi, diperlakukan seperti terpidana teroris atau lebih buruk lagi. Kami bukan bagian dari program rehabilitasi atau integrasi. Kami telah dibebaskan, tetapi kami belum menemukan keadilan.
Guantanamo telah dibuka selama lebih dari dua dekade. Dari 34 orang yang masih berada di penjara, 20 orang telah dibebaskan untuk dipindahkan – beberapa sudah lebih dari satu dekade. Tak satu pun dari mereka yang didakwa melakukan kejahatan, namun mereka masih terjebak di ruang penyiksaan Guantanamo.
Sebagai mantan napi, kami mengkampanyekan agar Guantanamo ditutup dan orang-orang yang masih ditahan di sana dibebaskan. Tapi kami juga menuntut keadilan.
Kami ingin pemerintah AS dimintai pertanggungjawaban atas penyiksaan dan pelecehan yang dilakukannya terhadap kami. Kami ingin kompensasi untuk semua kerusakan yang terjadi pada kami.
Apakah kita cenderung melihat keadilan dalam hidup kita? Mungkin tidak. Tapi kami akan terus berjuang, berkampanye dan protes – untuk ayah kami, Saifullah, dan semua saudara kami di dalam dan di luar kamp penjara.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi redaksi Al Jazeera.