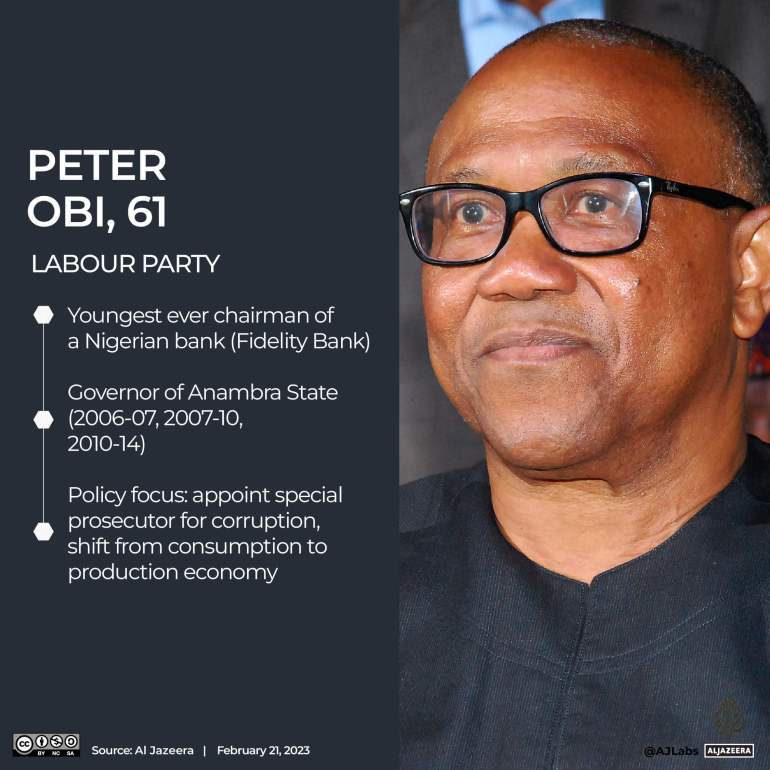Pada 7 Februari, polisi Kenya menangkap 41 migran Ethiopia tidak berdokumen dan dua penyelundup manusia di sebuah rumah. Nairobi.
Kelompok yang semuanya laki-laki, yang diyakini sedang dalam perjalanan ke Afrika Selatan, akan dituntut karena melanggar undang-undang imigrasi Kenya dan kemungkinan akan dideportasi ke Ethiopia.
Aneh kedengarannya, para migran ini seharusnya menganggap diri mereka beruntung telah ditangkap karena cobaan berat mereka di Kenya menghentikan mereka – setidaknya untuk saat ini – memulai perjalanan yang tidak pasti dan sangat berbahaya.
Antara tahun 2020 dan 2022, pihak berwenang di Mozambik, Malawi, dan Zambia menemukan mayat lebih dari 100 migran tidak berdokumen dari Ethiopia yang meninggal karena kelaparan atau mati lemas saat melakukan perjalanan diam-diam ke Afrika Selatan.
Menurut Organisasi Internasional untuk Migrasi, migrasi tidak teratur dari Tanduk Afrika ke Afrika Selatan sebagian besar “difasilitasi oleh jaringan penyelundup dan pedagang manusia yang rumit” yang “upaya agresif untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang menelan korban nyawa para migran alih-alih bahaya“.
Sebagaimana digariskan oleh Uni Afrika, orang bermigrasi di dalam Afrika karena “berbagai faktor yang mencakup kebutuhan akan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik melalui pekerjaan, faktor lingkungan, serta kelonggaran dari ketidakstabilan politik, konflik, dan perselisihan sipil”.
Migrasi tenaga kerja, dan terutama migrasi pekerja berketerampilan rendah, adalah sumber pergerakan paling konsisten di benua ini. Namun sebagian besar rezim imigrasi di Afrika tidak memiliki ketentuan visa untuk pekerja dan pengungsi ekonomi semacam itu, sehingga banyak imigran yang putus asa, seperti yang baru-baru ini ditangkap di Kenya, mencari bantuan dari penyelundup manusia untuk mencapai negara yang mereka anggap sebagai peluang kerja yang lebih baik.
Setelah mengambil risiko pribadi yang sangat besar untuk beremigrasi, migran yang tidak berdokumen dihadapkan pada serangkaian ancaman dan bahaya baru begitu mereka mencapai tujuan.
Di Afrika Selatan, misalnya, organisasi anti-migran Operasi Dudula memimpin kampanye dan tindakan yang ditujukan untuk membuat negara tersebut semusuh mungkin terhadap migran Afrika yang tidak berdokumen.
Sejak Januari, kelompok tersebut telah mencegah migran tidak berdokumen mengakses perawatan kesehatan di sebuah klinik di Johannesburg dan juga berusaha mengeluarkan anak-anak tidak berdokumen dari sekolah negeri di Diepsloot, pemukiman padat penduduk. Kelompok tersebut juga menargetkan migran yang menjalankan usaha kecil, kios pasar, dan toko swalayan informal di kota-kota dan pusat kota di seluruh negeri, menuntut agar mereka menutup toko dan pulang.
Migran di Afrika Selatan dan sekitarnya menghadapi tindakan permusuhan yang tidak masuk akal seperti itu meskipun para pemikir terkemuka dan politisi terkemuka Afrika telah berulang kali menyerukan agar tidak ada orang Afrika yang dianggap sebagai orang asing di mana pun di benua itu.
Misalnya, Julius Malema, pemimpin Partai Pejuang Kebebasan Ekonomi Afrika Selatan yang berapi-api, telah sering mengungkapkan sentimen ini, menyerukan benua itu untuk meruntuhkan perbatasan kolonialnya.
Demikian pula, PLO Lumumba, intelektual publik Kenya yang populer, berkata: “Tidak boleh ada negara Afrika yang menyatakan persona non grata Afrika mana pun, itu mengalahkan semangat persatuan Afrika.”
Pemikiran yang tercerahkan dan inklusif seperti itu mengagumkan, tetapi sayangnya tekad politik untuk memenuhi aspirasi bersama secara luas untuk Afrika tanpa batas masih belum cukup.
Pada Januari 2018, pertemuan Uni Afrika mengadopsi Protokol Perjanjian yang membentuk Komunitas Ekonomi Afrika mengenai pergerakan bebas orang dan hak tinggal dan pendirian.
Jika diratifikasi oleh setiap negara anggota, protokol ini akan memungkinkan orang Afrika untuk bekerja dan tinggal di negara Afrika mana pun tanpa memerlukan izin kerja. Namun agak mengecewakan, hanya 32 dari 55 negara di Afrika yang telah menandatanganinya sampai saat ini, dan hanya empat – Rwanda, Niger, São Tomé dan Principe dan Mali – yang telah meratifikasinya.
Perlawanan terus-menerus dari banyak pemerintah Afrika terhadap pergerakan bebas di seluruh benua, bersama dengan upaya mereka yang tidak praktis, tidak efektif, dan terkadang tidak manusiawi untuk mengawasi migrasi tidak teratur, menunjukkan kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap manfaat migrasi yang cukup besar.
Memang, migrasi – tidak teratur atau tidak – tidak hanya bermanfaat bagi para migran dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat yang menampung mereka.
Saya dapat bersaksi tentang fakta ini karena keluarga saya adalah produk dari migrasi tidak teratur.
Pada awal tahun 1930-an, kakek saya beremigrasi dari Watsomba, sebuah desa di Distrik Mutasa di Rhodesia Selatan (sekarang Zimbabwe), setelah apartheid Afrika Selatan.
Dia meninggalkan rumah hanya dengan tekad, etos kerja yang kuat dan pakaian di punggungnya.
Seorang pria dengan penghasilan yang sangat sederhana dan pendidikan yang tidak penting, dia memasuki Afrika Selatan di titik penyeberangan ilegal di Sungai Limpopo.
Dari sana dia melakukan perjalanan ke selatan Germiston, sebuah kota kecil di wilayah Rand Timur Gauteng, yang dikenal sebagai pusat ekonomi Afrika Selatan. Dia mendapat pekerjaan sebagai kurir dan pergi untuk tinggal di sana.
Setelah saya meninggalkan rumah, kakek saya mengunjungi Watsomba setiap lima tahun sekali. Dan setiap kali dia melakukannya, nenek saya mengandung seorang anak – semuanya lima. Penghasilan yang diperoleh kakek saya di Afrika Selatan membantu memberi makan, pakaian, dan pendidikan anak-anaknya, termasuk ayah saya.
Setelah 40 tahun bekerja di luar negeri, kakek saya akhirnya memarkir sepedanya untuk selamanya dan pulang ke rumah. Namun kembalinya kakek saya ke Zimbabwe bukanlah akhir dari hubungan keluarga kami dengan Afrika Selatan. Beberapa dekade kakek saya tinggal dan bekerja di Afrika Selatan mendorong banyak keturunannya untuk akhirnya pergi ke negara itu juga.
Cucu tertuanya menjadi dokter medis dan akhirnya memenuhi syarat sebagai ahli bedah ortopedi. Pada pertengahan 1990-an dia pindah ke Afrika Selatan dan bekerja di rumah sakit lokal di provinsi Limpopo.
Belakangan, cucu tertua keduanya, lulusan ekonomi dari Universitas Rhodes, pindah ke Afrika Selatan dan mendirikan beberapa bisnis sukses yang menghasilkan lapangan kerja bagi banyak orang Afrika Selatan.
Dan cicitnya lulus sebagai apoteker dari Universitas Rhodes dan mendapat pekerjaan di rumah sakit negara bagian di KwaZulu-Natal.
Saya bisa menguraikan berbagai hasil jerih payah kakek saya di rumah keduanya. Namun aspek terpenting dari kisah migrasi keluarga saya adalah ini: Pada tahun 1930, tak seorang pun dapat membayangkan bahwa seorang migran tanpa dokumen yang rendah hati dari sebuah desa terpencil di Zimbabwe akhirnya dapat mengembalikan tanah yang telah begitu banyak membantunya – dan yang dia layani dengan cara ini. Sehat.
Kisah keluarga saya hanyalah salah satu dari ribuan atau mungkin jutaan.
Orang Afrika Selatan yang terkenal seperti Albert Luthuli, Dorothy Masuka dan Jolidee Matongo berasal dari keluarga imigran.
Dan pada tahun 2020, rapper, pengusaha, dan petinju pemenang penghargaan Cassper Nyovest mengungkapkan bahwa kakeknya berjalan kaki dari Malawi untuk menetap di Potchefstroom, Provinsi Barat Laut.
Namun, ini bukan tentang Afrika Selatan.
Ini tentang inersia politik bencana Afrika.
Setiap tahun di seluruh Afrika, puluhan ribu orang jujur, pekerja keras seperti kakek saya terpaksa meninggalkan tanah air mereka untuk menghindari perang, ketidakstabilan politik, perubahan iklim, pemerintahan yang buruk atau kemiskinan dan membangun kehidupan baru untuk diri mereka sendiri di negara Afrika lainnya. Karena keadaan di luar kendali mereka, banyak dari orang-orang ini tidak memiliki dokumen. Mereka menghadapi permusuhan dari pihak berwenang dan berjuang untuk menjalani hidup mereka dengan bermartabat, apalagi berkontribusi pada komunitas baru mereka.
Ini adalah kerugian besar yang tidak perlu, tidak hanya bagi para migran ini dan keluarga mereka, tetapi juga negara adopsi mereka dan benua yang lebih luas.
Untuk kepentingan Afrika dan Afrika, apa yang disebut imigran “ilegal” harus segera dikenali, didokumentasikan, dan dilindungi dari bahaya eksploitasi ekonomi dan seksual, diskriminasi, dan xenofobia terorganisir yang tak terukur.
Hanya 3 persen penduduk Afrika yang tinggal di luar negara asalnya, jadi ini bukan tugas yang mustahil.
Tahun lalu, meskipun menginvestasikan miliaran dolar dalam teknologi pengawasan berteknologi tinggi, infrastruktur perbatasan, dan patroli darat dan laut, Amerika Serikat dan Uni Eropa sama-sama mengalami peningkatan eksponensial dalam migrasi tidak teratur.
Para pemimpin Afrika harus belajar dari kegagalan ini dan menerima bahwa dengan tidak adanya jalur migrasi resmi yang dapat diakses oleh semua orang yang rentan, termasuk migran ekonomi, migrasi tidak teratur tidak dapat diatur atau diberantas dengan sukses.
Mereka harus menghindari mempolitisasi migrasi ilegal dan sebagai gantinya menerapkan kebijakan yang mengakui dan memanfaatkan kecenderungan Afrika untuk bermigrasi di masa yang adil dan sulit.
Pada tahun 1963, Kwame Nkrumah, presiden pendiri Ghana, mengatakan, “Kekuatan yang menyatukan kita bersifat intrinsik dan lebih besar daripada pengaruh yang memisahkan kita.”
Sayangnya, perlu waktu untuk menyatukan Afrika dalam praktiknya dan membentuk benua bebas visa. Sementara itu, Uni Afrika harus bergerak untuk melindungi kehidupan dan mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan migrasi tak terbatas untuk sementara.
Dengan kemauan politik yang memadai, Afrika memiliki posisi yang baik untuk mengelola migrasi dengan cara yang aman, tertib, dan manusiawi.
Tidak ada orang Afrika yang harus mati untuk mencari kehidupan yang layak di Afrika.
Sudah saatnya Afrika meruntuhkan perbatasan kolonialnya.
Pendapat yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mencerminkan posisi redaksi Al Jazeera.