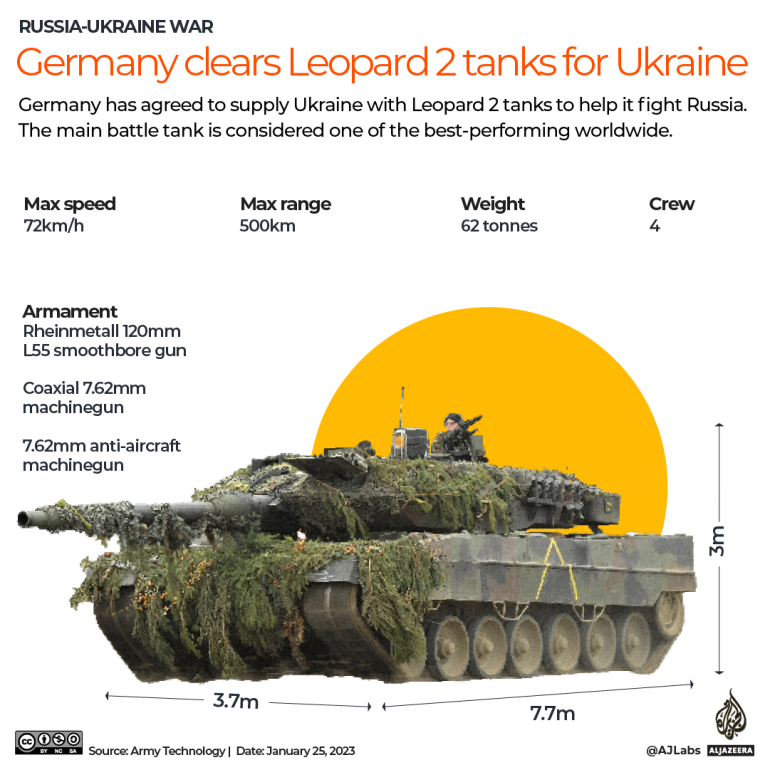Kaamil Ahmed, seorang jurnalis Inggris, telah meliput krisis Rohingya selama delapan tahun.
Saat ini menjadi reporter di The Guardian, dia telah melakukan beberapa perjalanan ke Bangladesh, di mana mayoritas Rohingya tinggal di pengasingan, untuk mendokumentasikan mata pencaharian orang yang dianggap sebagai salah satu yang paling teraniaya di dunia.
Penderitaan Rohingya selama beberapa dekade, yang dibuat tanpa kewarganegaraan oleh Myanmar pada tahun 1982, menjadi perhatian dunia pada tahun 2012, ketika kekerasan mematikan terhadap kelompok tersebut meletus di negara bagian Rakhine di negara Asia Tenggara – yang menyebabkan eksodus massal.
Penerbangan terbesar Rohingya terjadi lima tahun kemudian, ketika tentara Myanmar membunuh lebih dari 6.000 orang dan memaksa sekitar 700.000 orang menyeberang ke Bangladesh.
Menurut saksi mata dan kelompok HAM, tentara membakar dan meruntuhkan puluhan desa Rohingya dan menembak tanpa pandang bulu, membunuh perempuan dan anak-anak – peristiwa di mana pemerintah Myanmar dituduh melakukan genosida.
Buku Ahmed, I Feel No Peace: Rohingya Fleeing Over Seas and Rivers, adalah eksplorasi mendalam tentang Rohingya di pengasingan, eksploitasi mereka, mengejar keadilan, dan kegagalan nyata dari badan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi mereka.
Al Jazeera: Sebagian besar orang di dunia pertama kali menyadari Rohingya pada tahun 2012, ketika kekerasan mematikan pecah di Rakhine. Apa yang menarik Anda ke krisis?
Kamil Ahmad: Tepat sebelum 2012 ketika saya pertama kali bertemu Rohingya, saya belum pernah mendengar tentang mereka.
Saya melihat sebuah wawancara. Bahasanya agak tidak biasa. Ini mirip dengan Bengali tetapi ada beberapa perbedaan. Sangat menarik bahwa orang-orang ini ada yang belum pernah Anda dengar. Saya tertarik dan ingin memahami siapa mereka. Saya mulai lebih memperhatikan, membaca sebanyak mungkin tentang mereka.
Al Jazeera: Buku Anda mencakup asal-usul Rohingya, kekerasan selama puluhan tahun terhadap mereka dan undang-undang yang disahkan oleh negara Myanmar selama bertahun-tahun – seperti RUU tahun 1982 yang menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan. Ini juga mencakup perjalanan pengungsi mereka. Apa yang Anda harapkan terhubung dengan pembaca?
Ahmad: Buku-buku yang diterbitkan tentang Rohingya seringkali banyak berfokus pada Myanmar – dan saya tidak ingin menulis tentang Rohingya di Myanmar.
Saya ingin menceritakan tentang Rohingya sebagai pengungsi karena ada kisah penting yang perlu diceritakan tentang apa yang masih terjadi pada mereka di luar Myanmar… tetapi penting untuk memahami bagaimana mereka sampai pada titik ini – bagaimana tidak mengatasi semua hal yang terjadi dalam dekade (masa lalu) itu mengarah ke tempat mereka sekarang. Mereka dikembalikan dua kali, pada tahun 1978 dan pada tahun 1990-an… ketika ratusan ribu orang mayoritas pergi ke Bangladesh.
Mereka dikembalikan ke keadaan relatif tenang, tetapi tidak ke kedamaian atau keamanan. Badan-badan internasional dan semua orang yang bekerja dan memutuskan semua hal ini tentang kapan harus kembali… seperti “Oke, sekarang agak sepi”. Tak satu pun dari masalah mendasar diselesaikan. Undang-undang dan pembatasan, dan seluruh jenis negara polisi tempat mereka tinggal, tidak ada yang pernah ditangani.

Juga selalu ada pertanyaan ini – siapa mereka dan dari mana asalnya. Myanmar mengatakan mereka adalah penyerbu yang dibawa oleh Inggris.
Argumen itu didasarkan pada asumsi bahwa perbatasan tetap dan orang secara historis ditetapkan di tempat-tempat tertentu. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa perbatasan antara Bengal dan Arakan (Negara Bagian Rakhine) telah bergeser, begitu pula orang-orang di kedua sisi perbatasan tersebut. Populasi di kedua sisi memiliki pengaruh budaya dari begitu banyak tempat.
Al Jazeera: Selama pertemuan pertama Anda dengan seorang pria Rohingya, Nobi (bukan nama sebenarnya), pada tahun 2015 di sebuah kamp pengungsi Bangladesh, Anda menggambarkannya sebagai “gugup”, terutama di sekitar petugas keamanan. Jadi bagaimana Anda bisa membangun hubungan dengan komunitas?
Ahmad: Bersama waktu. Saya pergi (ke kamp pengungsian) berkali-kali dan menghabiskan beberapa minggu di sana. Saya tidak berbicara dengan mereka dan menghilang begitu cerita saya selesai. Saya terus datang kembali. Saya terus berbicara dengan mereka. Bahkan antara 2015 dan 2017, ketika saya tidak memiliki kesempatan untuk kembali, saya berbicara dengan Nobi melalui Facebook. Mendengarkan adalah hal yang paling penting. Itu bukan naskahnya… bagian yang Anda keluarkan. Inilah saatnya kami memberikan masukan.
Awalnya mereka memberi tahu saya hal-hal yang lebih mendasar… jenis umum bagaimana mereka hidup. Namun, ketika mereka menyadari saya akan kembali dan menghabiskan waktu, dan bersedia untuk terus berbicara dengan mereka, mereka akan terus memberi tahu saya lebih banyak. Mereka akan mendekati saya jika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan.
Al Jazeera: Otoritas non-Rohingia tidak benar-benar muncul dalam buku ini. Apakah itu disengaja atau apakah mereka sebagian besar menolak untuk berbicara?
Ahmad: Inti dari buku ini adalah tentang suara mereka (Rohingya), apa yang mereka katakan dan apa yang mereka alami. Tidak benar-benar apa yang ingin dikatakan para pejabat. Saya berbicara dengan mereka, saya tahu apa yang mereka katakan.
Al Jazeera: Penderitaan perempuan Rohingya telah didokumentasikan selama bertahun-tahun. Apakah menurut Anda mereka lebih rentan?
Ahmad: Saya kira demikian. Ada banyak wanita yang melajang karena berbagai alasan. Salah satu yang paling jelas adalah suami mereka dibunuh di Myanmar, jadi mereka datang sendiri (di Bangladesh dan di tempat lain).
Mereka mengurus anak mereka sendiri. Dan jika mereka mengasuh anak-anak mereka, sangat sulit bagi mereka untuk melakukan pekerjaan apa pun – karena tidak banyak pekerjaan yang boleh atau dapat mereka lakukan.
Dan jika ada pekerjaan, itu adalah pekerjaan kerja yang lebih disukai laki-laki. Sehingga mereka rentan karena tidak memiliki banyak penghasilan, dan tidak dapat meninggalkan anak karena tidak ada orang lain.

Di hampir semua kamp pengungsi atau tempat yang sangat miskin, banyak perekat sosial yang rusak. Orang-orang semakin putus asa.
Pialang menengah sangat aktif dan ada banyak cara kerjanya. Salah satu caranya adalah mereka akan berkata, “Kami dapat membawa Anda ke Thailand atau Malaysia”.
Pertanyaan lainnya adalah, “Mengapa Anda tidak datang dan bekerja untuk keluarga Bangladesh, sebagai pembantu rumah tangga?” Tapi kemudian Anda sampai di sana, Anda tidak dibayar dan Anda terjebak.
Pada tahun 2018, seorang pria Rohingya mendekati saya di kamp-kamp, dia mengatakan bahwa keluarganya telah melarikan diri dari Myanmar sebelum dia dan ketika mereka berada di kamp-kamp, istrinya, yang berjuang untuk hidup sendiri, diyakinkan oleh seorang pedagang untuk membiarkannya pergi. putri pergi bekerja untuk keluarga Bangladesh. Mereka diberitahu bahwa itu hanya beberapa bulan, tetapi gadis itu tidak diizinkan kembali dan keluarganya tidak dapat berkunjung.
Al Jazeera: Anda cukup kritis terhadap pemerintah Bangladesh dan kebijakannya terhadap Rohingya. Orang lain akan mengatakan negara yang dilanda kemiskinan itu dibebani pajak.
Ahmad: Pada akhirnya, jika kebijakan Bangladesh ketat dan membatasi, itu harus dilaporkan.
Saya juga berpikir bahwa Bangladesh terkadang dikritik tanpa mendapat dukungan. Ada sedikit amal yang sangat jelas di sana-sini, tetapi tidak ada dukungan yang substansial. Itu dalam posisi yang sulit dan itu… semakin sedikit bantuan. Karena anggaran menyusut, semakin sedikit bantuan dengan tuntutan yang lebih besar – populasi yang terus bertambah, orang-orang yang memiliki anak, diminta untuk mengajar.
Ketika Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh datang ke London, saya mewawancarainya, dan dia menegaskan – semua orang ingin kami memberikan program pendidikan (untuk Rohingya), tetapi tidak ada yang memberi kami uang bukan untuk itu.
Ini merupakan beban besar pada sumber daya dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan itulah inti dari buku ini… kurangnya bantuan internasional, kurangnya solusi nyata.

Al Jazeera: Apakah organisasi global yang harus disalahkan?
Ahmad: Ini adalah sesuatu yang benar di banyak tempat. PBB … akan sering tunduk pada tekanan dari pemerintah … untuk dapat melakukan dasar-dasar yang sebenarnya. Mereka harus menerima apa pun yang dilakukan pemerintah, dan tidak benar-benar menolak karena mereka hanya membutuhkan pemerintah untuk mengizinkan mereka berada di sana.
(Tapi) peran PBB tidak hanya untuk memberikan makanan dan tempat berlindung – mereka seharusnya melindungi orang dari pemulangan yang tidak aman.
Fakta bahwa pada 1990-an, mereka sendiri laporan menyarankan mereka memiliki peran dalam orang yang dikembalikan secara paksa, itu adalah masalah yang perlu diangkat.
Al Jazeera: Apa inti utama dari buku Anda?
Ahmad: Apa yang terjadi pada Rohingya tidak terjadi dalam satu atau dua bulan. Itu tidak berhenti atau dimulai dengan pembantaian. Itu terjadi selama beberapa dekade.
Ini adalah orang-orang yang benar-benar terpinggirkan dan dikucilkan. Dan itu berlanjut ke luar negeri. Begitu mereka menjadi pengungsi, itu tidak berhenti.
Ke mana pun mereka pergi, mereka dieksploitasi – oleh orang-orang, geng narkoba, pedagang manusia, dan pemerintah. Tidak ada pemukiman kembali untuk mereka, tidak ada kewarganegaraan. Jadi mereka benar-benar macet, sama sekali tanpa kewarganegaraan.
Anda hampir dapat memetakannya, ke mana pun mereka pergi, ada seseorang, beberapa elemen kriminal di sepanjang jalan, mengeksploitasi mereka. Itu adalah kekerasan yang terus-menerus.
Catatan editor: Wawancara ini telah diedit dengan ringan untuk kejelasan dan singkatnya.